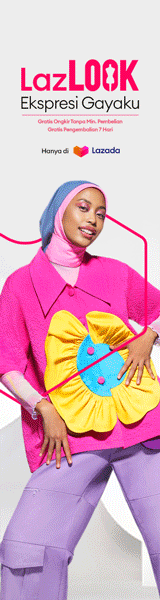Logam Tanah Jarang; Masa Depan Hijau yang Kotor

Di dalam tanah, terkandung kekayaan. Itu sudah lama kita tahu. Tapi jarang kita bertanya: untuk siapa kekayaan itu? Dan untuk apa ia digali?
Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, dalam satu pertemuan resmi di Mamuju, menyebut logam tanah jarang (LTJ) sebagai hal baru baginya. Ia menyebutnya “panah sebagainya.” Saya tak hendak mengolok kekeliruan lidah atau ketidaktahuan seorang pejabat karena siapa pun bisa keliru. Tapi dari pernyataan itu, tampak satu kecenderungan lama yang tak lekang dalam politik pembangunan kita: mengagumi sebelum mengerti, menawarkan sebelum memahami, menggali sebelum bertanya.
Logam tanah jarang adalah nama yang tak asing bagi para insinyur pertahanan, pengembang kendaraan listrik, atau perusahaan teknologi tinggi dari Silicon Valley sampai Beijing. Tapi bagi petani di Polewali Mandar dan nelayan di Mamuju, nama itu masih menggantung seperti pertanyaan yang belum dijawab: apa yang akan terjadi jika tanah mereka dijadikan proyek besar tambang nasional?
Logam tanah jarang adalah kelompok dari 17 unsur kimia, dengan nama-nama eksotis seperti neodymium, dysprosium, dan cerium. Mereka dibutuhkan untuk magnet super kuat dalam turbin angin, layar ponsel, dan bahkan sistem senjata presisi tinggi. Dunia modern menyebutnya sebagai bahan dasar “masa depan hijau.” Tapi logam-logam ini tidak hadir dengan wajah sebersih yang dijanjikan. Ia hadir dengan lumpur, dengan limbah asam, dengan air beracun, dan sering kali dengan konflik sosial.
Jika menteri ingin tahu apa yang akan terjadi jika LTJ dikeruk tanpa perhitungan, ia tak perlu membaca buku tebal. Cukup melihat Baotou, Mongolia Dalam, Tiongkok, yang kini dijuluki “kota mati logam tanah jarang.” Di sana, pertambangan LTJ berlangsung selama puluhan tahun. Tanah menjadi keras dan tandus, air menghitam, dan danau limbah beracun menjadi pemandangan sehari-hari. Penduduk melaporkan meningkatnya kasus kanker, penyakit kulit, dan bahkan anak-anak yang lahir dengan kecacatan. Sebuah studi oleh Chinese Research Academy for Environmental Sciences menyebut bahwa logam tanah jarang meninggalkan bekas radioaktif dan bahan kimia beracun seperti thorium dan uranium dalam jumlah tinggi.
Kasus serupa terjadi di Bukit Lynas, Malaysia. Pemerintah Malaysia pernah menghadapi protes besar ketika sebuah pabrik pengolahan LTJ yang bekerja sama dengan perusahaan Australia dibangun di Kuantan. Protes itu bukan tanpa alasan: pengolahan logam tanah jarang menghasilkan limbah radioaktif, dan perusahaan tidak mampu menjamin sistem pembuangan limbah yang aman.
Di Myanmar utara, perbatasan Kachin dan China, tambang-tambang LTJ ilegal dikuasai milisi bersenjata. Setiap kilogram LTJ yang diekspor ke Tiongkok berarti satu jejak kekerasan di pedalaman Asia Tenggara. Di Republik Demokratik Kongo, perburuan logam untuk baterai dan komponen elektronik juga melibatkan kerja paksa anak-anak dan perang antar faksi. Inilah wajah kelam dari energi masa depan: hijau di layar presentasi, merah di tanah yang digali.
Tak salah jika menteri menyebut Amerika Serikat ingin masuk ke pasar LTJ Indonesia, keinginannya benar adanya. Sejak Tiongkok mengontrol lebih dari 70% pasokan LTJ global, negara-negara Barat mulai panik. Amerika, Jepang, dan Uni Eropa kini berusaha mencari pasokan baru: Australia, Afrika, dan tentu saja Indonesia.

Tapi ada satu hal yang mesti kita sadari: ketika kekuatan global mulai melirik kekayaan kita, itu bukan pujian, itu peringatan. Mereka datang bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai pemodal dengan kepentingan. Mereka datang membawa teknologi, tapi juga perjanjian dagang yang kerap tidak adil. Di tengah pertarungan itu, di manakah posisi masyarakat Sulbar? Di manakah suara petani, nelayan, dan perempuan desa yang akan terdampak langsung?
Negara kerap menyebut masyarakat jangan jadi penonton. Tapi bagaimana bisa jadi pemain jika naskahnya sudah ditulis tanpa partisipasi mereka? Pemerintah akan mengirimkan Tim Ekspedisi Patriot, katanya untuk “meningkatkan kapasitas masyarakat.” Tapi peningkatan kapasitas yang dilakukan dari atas, tanpa dialog dan persetujuan yang bebas, sadar, dan didahulukan, adalah tipu daya dengan nama lain.
Kita telah melihat luka itu di Morowali. Investasi tambang nikel disebut membawa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah ke dua digit, bahkan 16 persen. Tapi dalam data yang sama, angka kemiskinan pun meningkat. Pertumbuhan yang tak merata hanya memperkaya segelintir elit dan mengusir rakyat dari tanahnya.
Mereka kehilangan mata air, sawah, dan udara bersih. Di banyak titik, buruh migran menggantikan penduduk lokal. Yang tersisa hanya kebisingan mesin dan harga sembako yang melambung.
Apakah Sulawesi Barat ingin mengulang naskah yang sama? Tanpa kehati-hatian, tanpa analisis ekologi mendalam, dan tanpa perencanaan partisipatif, maka proyek LTJ hanya akan jadi babak baru dari sejarah panjang kolonialisme sumber daya: dari rempah, ke emas, ke batubara, dan kini ke logam tanah jarang. Nama-namanya berubah. Tapi korbannya selalu sama, yakni rakyat kecil.
Tanah bukan sekadar sumber daya. Ia adalah ruang hidup, ruang budaya, dan ruang kenangan. Di sanalah anak-anak belajar bicara dan menanam, di sanalah makam-makam tua menunggu ziarah dan doa, di sanalah ibu-ibu menumbuk padi, bukan bijih logam.
Ketika sebuah tambang masuk, bukan hanya tanah yang hilang. Juga bahasa, relasi sosial, ritme hidup, masa depan, dan lidah yang tak lagi bisa mengecap manis hasil panen. Kita kehilangan sesuatu yang tak bisa dihitung dengan rumus ekonomi: kehilangan rasa memiliki.
Pertanyaan yang mendesaknya: apakah energi bersih bisa disebut “bersih”, jika tanah tempat logamnya ditambang justru makin kotor secara fisik maupun moral?
Gunawan Mohamad pernah menulis bahwa kita sering “membangun peradaban, tapi lupa mendengarkan suara batu.” Dalam hal ini, kita membangun teknologi, tapi melupakan suara tanah, air, dan tubuh-tubuh yang menjadi korbannya.