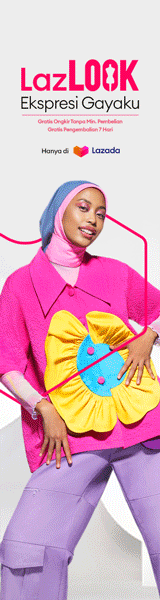Dari Lereng Ratte, Loko Mengajarkan Ketahanan Pangan

Sebuah potret gubug kecil yang berdiri tegak di setiap ladang warga, dengan dinding papan, atap yang terbuat dari daun sagu, dan empat tiang sebagai penyangga. Sekilas, ketika kita berjalan melewati ladang milik warga, gubug kecil ini terlihat bagaikan rumah kebun yang ditempati untuk beristirahat oleh petani, karena bentuknya yang hampir mirip dengan rumah pada umumnya. Tetapi yang membedakan ialah ukurannya yang minimalis, membuat saya dan mungkin pembaca sendiri tertipu akan hal itu.
Ia masih berdiri kokoh dan tetap eksis hingga sekarang. Sebuah pelestarian dari warisan leluhur ini menggambarkan bagaimana para pendahulu mereka tetap bisa survive dalam menjalani hidup, dengan berbekal pengalaman dan kepiawaiannya menciptakan sebuah inovasi bertahan hidup di tengah hiruk pikuk perekonomian yang terbatas.
Ratte, desa kecil yang terletak di lereng-lereng pegunungan, hanya bermodalkan pengetahuan alam dan pengamatan itu mampu menembus benteng-benteng seleksi alam. Gubug minimalisnya pun menjadi saksi bagaimana peradaban kecil ini terbentuk dengan nilai dan budaya yang masih bertahan sampai sekarang di tengah modernitas yang mengekspansi wilayah ini. Ia bukan hanya rumah yang tak berpenghuni, tetapi sebagai sahabat yang tetap setia menemani hingga lintas generasi.
Gubug itu bernama Loko. Ia berfungsi untuk menyimpan hasil panen padi. Kemudian, dari isi loko itu diambil secara berangsur-angsur ketika masyarakat membutuhkan padinya untuk diolah dan dimakan. Sebuah cara ketahanan pangan yang dimiliki oleh masyarakat sebagai warisan tua dan sangat berharga yang tetap dilestarikan, sebab fungsinya yang vital memberikan masyarakat Ratte penghidupan untuk tetap bisa menatap kehidupan selanjutnya.
Selain daripada fungsinya yang begitu vital, ia juga sebagai simbol yang menggambarkan bagaimana kesyukuran dan penghormatan terhadap pemberian alam tercantum dalam proses-proses ritual yang berbasis tradisional.
Padi yang telah dipanen itu diikat beberapa bagian, kemudian dikeringkan menggunakan alat yang dibuat oleh warga lokal yang mereka sebut dengan nama tara’de, sebuah alat pengeringan khas masyarakat lokal di sini yang sangat berbeda dari apa yang kita lihat pada umumnya. Alat pengeringan tara’de semacam rangka yang dibuat untuk wadah padi ketika ingin digantung. Jadi, proses pengeringannya itu digantung. Bukan hanya itu, proses pengeringannya pun juga berbeda. Padi gunung semacam ini perlu waktu yang agak lama agar padinya siap dimasukkan dalam loko. Kata Bapak Budi selaku warga lokal, “20 hari biasanya sebelum mau dikasih masuk dalam loko.”
Setelah kering, masyarakat kemudian memanggil sando pare untuk melakukan tahapan ritual sebelum dimasukkan dalam loko, rasa syukur dan doa agar kebutuhan pokok mereka diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Pemberi. Rasa syukur dipanjatkan bahwa padi yang berada di loko ini sebagai pertanda tentang kelimpahan rezeki yang diberikan oleh Tuhan melalui ciptaan-Nya, yaitu alam.
Tapi saya tidak akan begitu membahas bagaimana sando pare ini secara detail. Selain karena informasi tentang sando pare ini minim, saya juga masih fokus pada pembahasan tentang loko.

Pertanyaannya, setelah kemudian padi itu sudah berada dalam loko dengan berbagai jenisnya, apakah ia akan bertahan hingga satu tahun ke depan untuk mendapatkan hasil panen selanjutnya? “Tergantung, biasa ada acara, atau biasa juga lahan yang dibuka sedikit, jadi tidak cukup untuk satu tahun,” ujar Bapak Budi. Bapak Budi sendiri sudah dua tahun tidak membuka lahan untuk penanaman padi, ia berfokus menanam nilam yang kebanyakan ditanam oleh warga sekitar.
Tetapi mayoritas warga masih mengharap ladang padi ini sebagai sumber kebutuhan pokok mereka dan masih mempertahankan kebudayaan ini. Itu terbukti dari apa yang disampaikan oleh Bapak Budi, “Ya, masih banyak ji juga orang menanam padi kalau waktunya sudah tiba, dan biasa isi loko-nya itu bertahan sampai satu tahun ke depan.”
Keterangan Bapak Budi di atas menggambarkan tentang bagaimana isi dari loko ini akan bertahan sampai setahun lamanya ketika tidak ada halangan lain yang memungkinkan ia tidak mencapai panen selanjutnya. Tetapi yang ingin saya sampaikan dalam tulisan singkat ini, bahwa ketahanan pangan dengan menggunakan loko sangat efektif bagi masyarakat Desa Ratte, sebab inilah yang digunakan oleh leluhur mereka dalam mengarungi bahtera kehidupan.
Loko bukan sekadar bangunan kecil di tengah ladang. Ia adalah simbol dari peradaban lokal yang kuat, tangguh, dan berakar dalam nilai-nilai kearifan tradisional. Di balik kesederhanaannya, loko menyimpan makna besar tentang ketahanan pangan, penghormatan terhadap alam, dan kebijaksanaan leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam loko, kita menemukan sebuah narasi yang jauh lebih besar dari sekadar tempat menyimpan padi. Ia adalah cermin dari kehidupan masyarakat Ratte yang harmonis dengan alam dan sesama.
Di tengah arus modernisasi yang perlahan menembus batas-batas pedalaman, loko tetap berdiri, menjadi saksi bisu bahwa warisan tradisi dan inovasi lokal mampu bertahan melintasi zaman. Ia mengajarkan kepada kita bahwa ketahanan pangan bukan hanya tentang teknologi dan kebijakan, tapi juga tentang kedekatan dengan tanah, penghormatan terhadap hasil bumi, dan nilai-nilai spiritual yang menyertainya.
Loko adalah wajah dari Desa Ratte—desa yang sederhana, tapi kaya akan makna. Dari tangan-tangan petani, dari sando pare yang menjaga, dan dari alam yang memberi, loko terus menghidupi dan menjaga denyut kehidupan masyarakatnya. Sebuah pelajaran penting tentang bagaimana manusia dan alam dapat berjalan seiring dalam harmoni yang tak lekang oleh waktu.