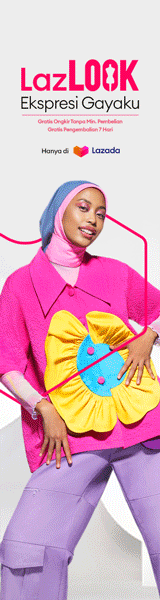Mistisme dan Moderenisasi di Buttu Dakka

Jauh sebelum kota Wonomulyo berpenghuni, Buttu Dakka telah menjadi rumah bagi beragam manusia dari berbagai latar belakang etnis. Bahkan di masa penjajahan, kampung ini kerap dikunjungi oleh para petinggi Belanda setingkat kecamatan. Mereka datang bukan hanya untuk menjalin relasi dan keakraban, tetapi juga untuk membeli tanah milik penduduk lokal.
Kala itu, Buttu Dakka telah melegenda sebagai ruang pertemuan antara sakralitas alam dan dinamika masyarakat lokal. Dalam konteks masyarakatnya, zaman mistik bukan sekadar masa lalu yang penuh cerita horor, melainkan sebuah era yang menandai kedekatan manusia dengan alam dan dimensi spiritual.
Ritual tara‘ duduk bersila sambil memejamkan mata untuk memohon sesuatumenjadi praktik umum yang dilakukan sebagian warga menjelang dini hari. Fenomena ini mencapai puncaknya pada akhir 1980-an, saat porkas (permainan undian) menjadi primadona masyarakat. Bagi pelakunya, tara’ bukan sekadar ritual, melainkan ekspresi harapan dan komunikasi batin dengan kekuatan tak kasat mata.
Ritual lainnya seperti melepas nazar, membakar kemenyan, dan makan bersama di kaki Gunung Buttu Dakka menjadi bagian dari tradisi tahunan masyarakat setempat. Bahkan saluran irigasi yang membelah Kecamatan Wonomulyo dan Tapango tak hanya berfungsi sebagai batas geografis, tetapi juga menjadi pusat pelaksanaan ritual tertentuseperti melepas ayam atau kambing sebagai simbol pelepasan nazar, yang diyakini sebagai bentuk pengharapan akan keberkahan.
Menariknya, ritual-ritual semacam ini tidak hanya dilakukan oleh warga lokal, tetapi juga oleh orang-orang dari luar kampung Buttu Dakka. Mereka datang membawa harapan dan nazar masing-masing. Hampir setiap pekan, wilayah ini menjelma menjadi panggung spiritual terbuka, tempat berbagai komunitas berkumpul untuk berdoa, makan bersama, dan melakukan pelepasan simbolik.
Bagi warga lokal, momen-momen tersebut membawa keberuntungan tersendiribukan hanya secara spiritual, tetapi juga secara sosial dan ekonomi. Mendapat ayam atau kambing dari ritual nazar, atau sekadar menikmati hidangan gratis, menjadi berkah tersendiri di saat daging ayam hanya bisa dinikmati kala hajatan atau lebaran tiba.
Namun, seiring perubahan zaman, kehadiran modernisasi mulai menggeser ruang-ruang sakral ini. Pembangunan infrastruktur dan kebijakan pemekaran wilayah membawa perubahan yang signifikan. Peran manusia dalam menjaga sakralitas alam pun perlahan tergantikan oleh mesin dan sistem birokrasi.


Ritual-ritual yang dahulu semarak kini kian jarang dijumpai, tergantikan oleh aktivitas yang lebih pragmatis dan berorientasi pada efisiensi. Meski jejak mistik dan spiritualitas Buttu Dakka masih bertahan dalam ingatan sebagian masyarakatnya, namun sejauh ini, belum ada upaya kreatif yang dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap arus homogenisasi budaya yang hadir menyertai modernisasi.
Modernisasi dan rasionalisasi kehidupan telah mengubah segalanya. Gema nilai-nilai lokal perlahan meredup, terdesak oleh tuntutan zaman yang semakin rasional dan seragam. Tatanan budaya yang dulu mengakar kuat kini tampak tak berdaya menghadapi gempuran perubahan.
Demikian pula, hamparan sawah yang dulu menguning dan menjadi simbol kemakmuran serta keterhubungan manusia dengan alam, perlahan digantikan oleh narasi industrialisasi dan bayang-bayang kemiskinan.
Sungai yang dulunya menjadi sumber kehidupan itu, kini berubah menjadi cermin suram dari kerusakan lingkungan. Air jernih yang dahulu memantulkan semangat hidup dan keceriaan generasinya, kini mulai keruh, tercemar oleh limbah plastik yang tak kunjung henti.
Popok bayi, botol plastik, sandal jepit, sepatu bekas, hingga kemasan belanja daring berserakan di aliran sungai, seolah menjadi penanda bisu akan pergeseran nilai dan gaya hidup masyarakat yang abai terhadap alam.
Ritual-ritual lokal yang dahulu memaknai harmoni manusia dan alam perlahan memudar, seolah terkubur oleh modernisasi dan budaya konsumtif. Bahkan di tempat-tempat sakral, di mana sesajen pernah diletakkan, kini posisinya tergantikan oleh sampah domestik.
Padahal, harmoni dengan alam sejatinya adalah warisan berharga yang harus dijaga, bukan dikorbankan atas nama kemajuan. Sebab Buttu Dakka bukan sekadar kampung, melainkan cermin dari dinamika budaya yang kompleksantara mistik dan modern, antara spiritualitas dan pembangunan. Buttu Dakka mengajarkan kita bahwa budaya bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita memaknai masa kini dan masa depan.
Penulis: Suaib Prawono
Warga biasa yang kebetulan diamanahi sebagai Koordinator Wilayah GUSDURian Sulawesi, Maluku dan Papua (Korwil GUSDURian Sulampapua